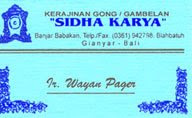Jaman sekarang tepat dikatakan era instant. Artinya segalanya diharapkan serba cepat, jauh melebihi kecepatan proses normatif. Tak terbatas pada produk – produk makanan atau sejenis lainnya. Pewujudan karya seni pun demikian adanya. Hingga pemotongan proses secara semena – mena, mengkontaminasi kwalitas seni yang dihasilkan. Misal instanisasi semena – mena yang terjadi dalam perkembangan seni tari.
Seni tari di kantong – kantong wilayah pewaris seni budaya / tradisi di bumi nusantara ini, diyakini berkembang secara serempak tanpa ada komando. Dinamika ini terjadi oleh tuntutan jaman instant semena – mena itu, hingga seni tari bersumber pada tradisi pun, ikut-ikutan kena himbas instanisasi. Seperti mempercepat proses penciptaan, pembentukan dan penuangan sebuah karya tari, akibat kejar tayang. Menggunakan alat bantu (property) secara berlebihan dan sebagainya. Padahal dari berbagai proses yang diabaikan, justru membuat kurangnya kwalitas pentas seni tari itu dari berbagai aspeknya.
Dari percepatan proses penciptaan, pembentukan dan penuangan sebuah tari akibat kejar tayang, adalah sebuah proses yang sebenarnya bertolak belakang dari hakikat pewujudan karya seni tari tradisi, atau bersumber pada tradisi jaman sebelum ini. Sebab seniman sebelumnya berkarya atas inspirasi yang sangat pribadi, yang dijajal dalam kematangan proses dan tanpa di intimidasi waktu. Proses ini tentu telah diuji coba dalam berbagain situasi, sampai pencipta merasakan kepuasan dari berbagai aspeknya. Kemudian dipublikasikan dalam bentuk karya tari standar dari berbagai aspeknya.
Dari penampilan secara umum, karya tari dulu tampak sangat sederhana, baik dari kostum maupun komposisi tarinya. Kemudian selalu tampil memukau dan mudah dikembangkan, tentu karena kematangan proses itu. Seperti misalnya komposisi - komposisi tari di
Kemudian tari dalam sendratari juga demikian. Di Bali belakangan ini boleh dikatakan sendratari terwujud hanya untuk konsumsi PKB (Pesta Kesenian Bali) saja. Anehnya, penampilan glamornya di stage terbuka Ardha Chandra Denpasar, justru berada dalam kesemuan karya seni khususnya seni tari. Penggunaan property berlebihan adalah penyebab utamanya. Bayangkan saja, penari yang seharusnya berekspesi gagah, tiba – tiba berwajah ketakutan, karena property gajah yang ditungganginya, tersandung lipatan karpet alas stage. Dan banyak kejadian lucu lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada sosialisasi sebuah karya tari selanjutnya.
Coba diingat, sedikit dari banyak sekali sendratari produk PKB, dapat berkembang di masyarakat umum. Hanya karena mereka minim biaya atau tak punya panggung luas. Lain dengan sendratari sebelum jaman ini. Amoman membakar Bumi Alengka hanya dengan gerak dan ekspresi, bukan membawa obor. Rajapala pun mengintip tujuh bidadari mandi seolah telanjang dalam air. Demikian juga karya tari sejaman lainnya.
Tanpa ada niat mempersalahkan pihak – pihak didalamnya, peristiwa ini serentak terjadi di daerah – daerah pewaris seni berakar tradisi itu. Maka sudah sepatutnya diupayakan untuk menimalisir kemudian memberanguskan hal – hal yang senantiasa wujudkan kemanjaan berkesenian, hingga sampai pada penyusutan kwalitas karya seni, seni tari pada khususnya.
Moga tulisan ini mampu membuat pihak – pihak berkompeten terjaga dari buaian negatif jaman instant ini dengan komitmen tanpa jeda tawar. Khusus untuk di Bali, penterjagaan buaian ini, telah disepakati masing – masing kabupaten dan